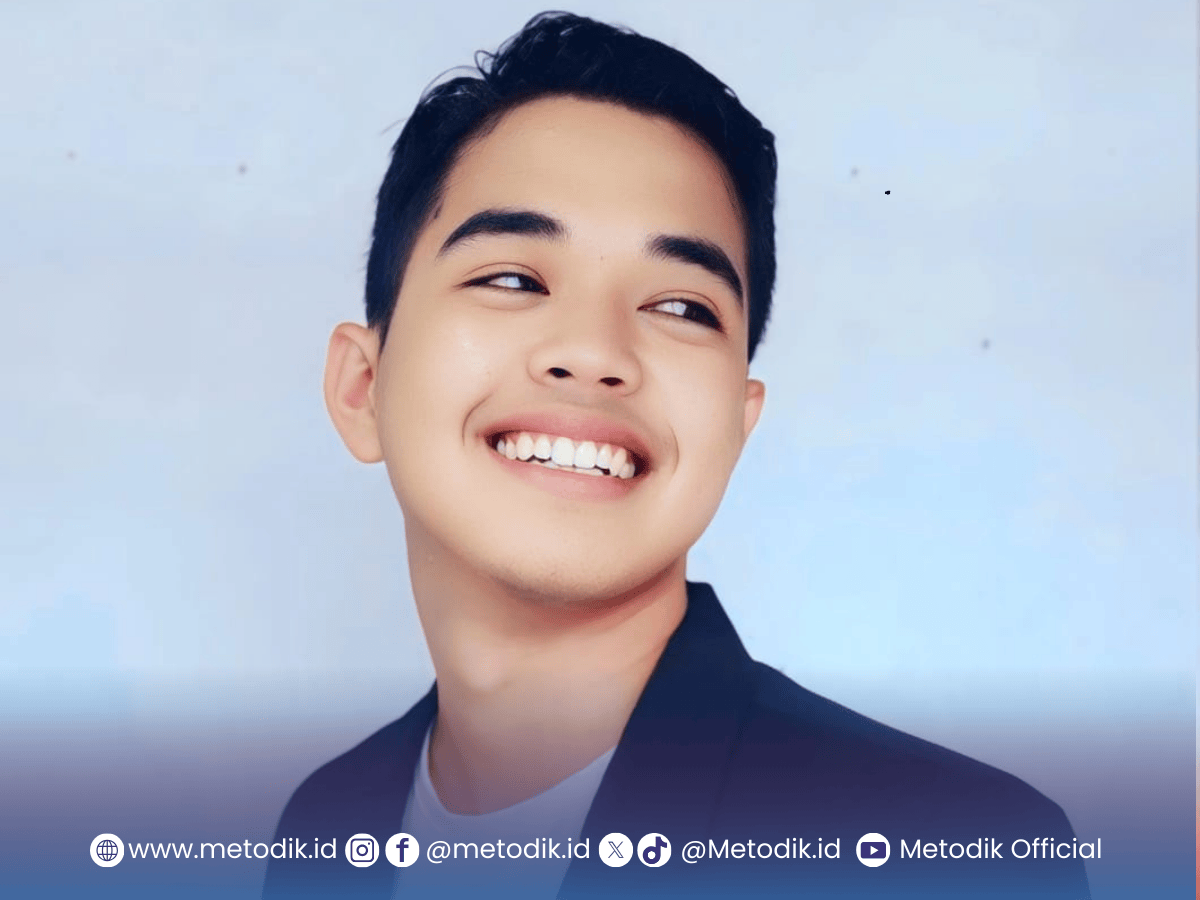
Oleh: Hariz A'Rifa'i, S.Pd., M.I.Kom.
Negara ini memang unik. Ketika rakyat mengeluh soal harga beras, pemerintah jawab dengan statistik. Ketika rakyat teriak soal pajak dan upah kecil, DPR malah naikkan tunjangan. Dan ketika seorang pengemudi ojek online tewas dilindas mobil Brimob saat demo di Senayan, responsnya? Biasa saja, seolah itu bagian dari SOP.
Affan Kurniawan, 21 tahun, bukan demonstran. Ia sedang lewat, mungkin mau pulang, mungkin sedang kejar order. Tapi roda kendaraan taktis Brimob berhenti di atas tubuhnya. Lalu keluar pernyataan normatif: akan diselidiki. Ya, sudah tahu akhirnya akan dikubur di laporan internal. Sementara publik geram, elite negara lebih sibuk jaga wibawa citra.
Di sisi lain, para wakil rakyat di Senayan malah sibuk menjelaskan soal tunjangan rumah Rp50 juta per bulan. Iya, lima puluh juta. Katanya bukan naik, hanya penyesuaian karena tak lagi dapat rumah dinas. Masuk akal, kalau rakyat juga bisa hidup wajar. Tapi ketika tukang parkir, buruh, dan pedagang asongan sedang dihimpit pajak dan harga-harga, yang terasa bukan logika—tapi tamparan.
Lucunya lagi, Wakil Ketua DPR Adies Kadir dengan enteng menyebut tunjangan beras naik ke Rp12 juta dan bensin Rp7 juta. Sontak publik ngamuk. Tapi Adies buru-buru bilang salah sebut. Oh, baik. Di negeri ini, salah sebut ternyata bisa menghanguskan nalar publik. Salah ucap pejabat bukan sekadar kekeliruan, tapi pertunjukan bagaimana elit meremehkan kemarahan rakyat.
Tak mau kalah, Ahmad Sahroni, anggota Komisi III DPR dari NasDem, ikut tampil. Dia bilang, orang yang ingin DPR dibubarkan itu “tolol sedunia.” Mungkin menurutnya itu lucu. Atau mungkin dia lupa kalau tugas DPR itu mewakili rakyat, bukan mengejek rakyat. Kalau ada warga marah, justru tugasnya mendengar, bukan menghina. Tapi ya, barangkali dalam dunia mereka, kritik dianggap gangguan. Bukan koreksi.
Lalu muncul komentar dari Nafa Urbach, anggota DPR dari NasDem, yang dengan polos menyatakan, “Kami juga manusia. Kami butuh kontrak rumah.” Betul, semua manusia. Tapi barangkali beliau lupa, manusia yang sama sedang antre sembako dan makan mie instan tiga hari berturut-turut.
Dan ketika kemarahan publik makin panas, negara bukannya introspeksi—malah sibuk panggil TikTok dan Meta. Katanya platform itu terlalu banyak menampung konten keresahan. Luar biasa. Ini seperti menyalahkan toa masjid karena terlalu banyak orang mengeluh ke Tuhan.
Kalau kita lihat dari sudut komunikasi politik, apa yang terjadi ini jelas contoh sempurna dari kegagalan komunikasi massa yang fatal. Elit politik yang seharusnya menjadi mediator antara kebijakan dan rakyat malah jadi sumber kebisingan dan kegaduhan. Mereka mengadopsi pola komunikasi top-down yang monologis dan penuh defensif, yang hanya memperlebar jurang ketidakpercayaan.
Ini yang disebut ‘political tone-deafness', ketulian elit terhadap denyut nadi publik. Alhasil, narasi mereka tak menyentuh hati, justru memantik kemarahan. Dalam kondisi seperti ini, komunikasi politik tidak lagi soal menyampaikan pesan, tapi soal kemampuan menjadi bagian dari dialog sosial. Yang terjadi sekarang? Mereka bicara tentang rakyat, tapi lupa bicara dengan rakyat.
Jadi, kalau hari ini rakyat turun ke jalan, itu bukan sekadar protes biasa. Itu adalah alarm keras dari komunikasi politik yang gagal. Kalau negara ingin kembali dipercaya, jangan cuma sibuk jaga citra dan panggil platform medsos. Mulailah dengar, turunkan nada, dan bicaralah dengan bahasa yang dimengerti rakyat. Karena bicara tanpa didengar, sama saja berteriak di hutan, lelah, sia-sia, dan akhirnya membuat semuanya rusuh.




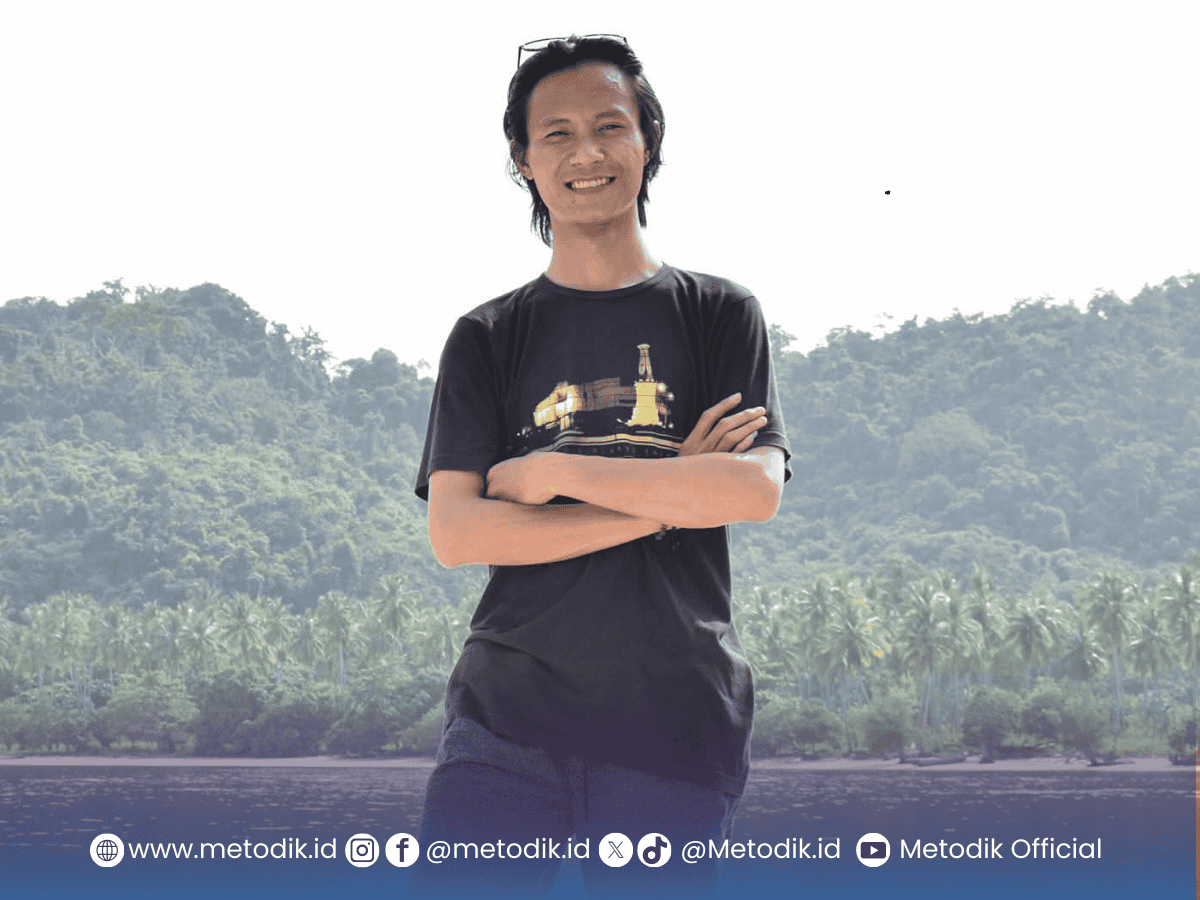

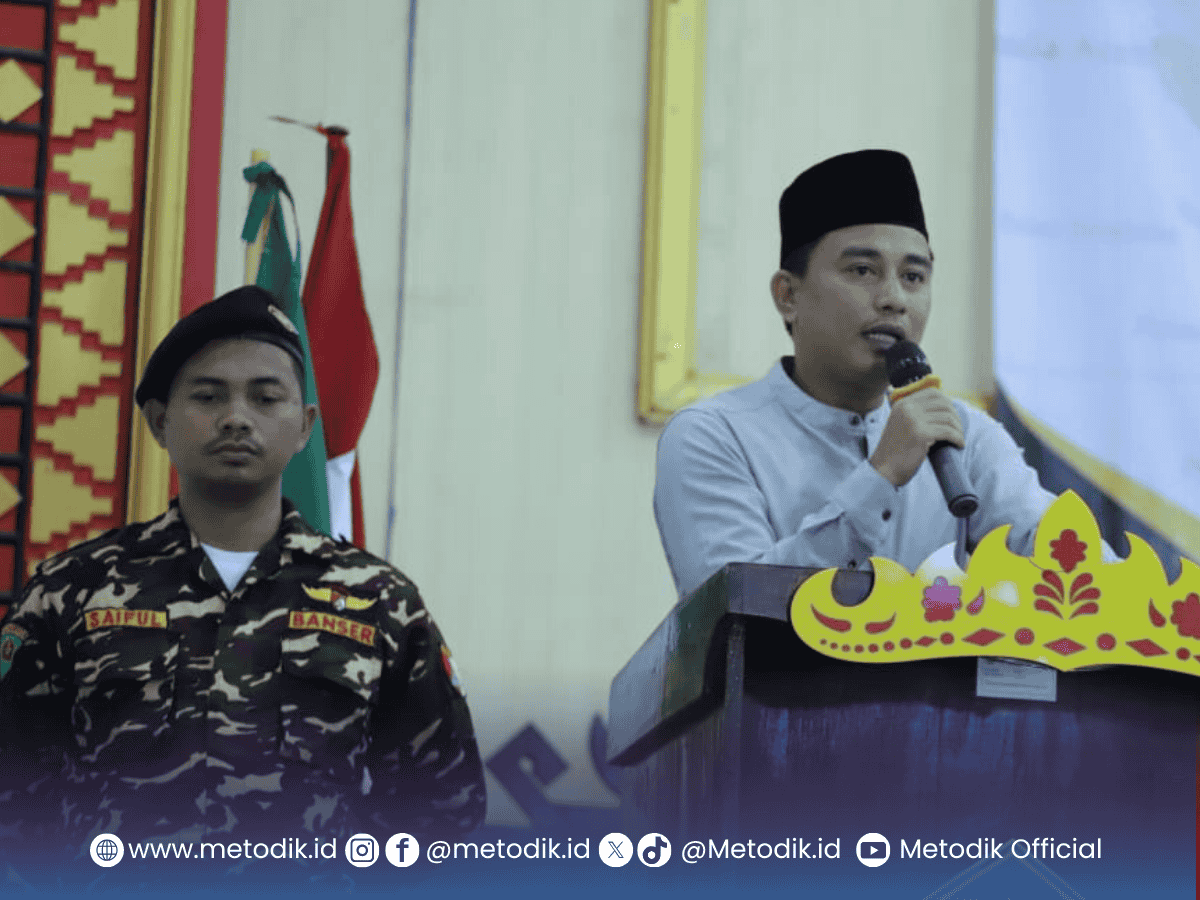

Komentar
A: Sangat informatif, terima kasih atas beritanya!
B: Semoga vaksin PMK ini bisa membantu peternak di Lampung.